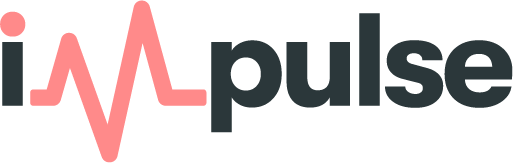Sudah cukup banyak kasus pengusaha makanan yang kelimpungan ketika diserang isu bahwa produknya tidak halal. Salah satu kejadian yang melekat di ingatan saya adalah restoran Solaria. Selama beberapa tahun restoran ini tumbuh dan berkembang dengan banyak pelanggan, lalu beberapa tahun yang lalu merebak isu bahwa restoran ini memakai bahan baku/bumbu yang tanpa label halal. Sontak pengelola restoran ini kelimpungan.
Mereka terancam kehilangan pelanggan. Tidak hanya itu, ada pula risiko menjadi sasaran kebencian. Buru-buru mereka mengurus sertifikat halal yang dikeluarkan LPPOM-MUI.
Hal yang sama terjadi pada produk mie Samyang. Importir produk ini mengaku bahwa produknya sudah mendapat sertifikasi halal di Korea. Tapi karena sudah beredar isu bahwa produk ini mengandung babi, maka terjadi guncangan. Ada potensi bahwa konsumen akan berhenti membelinya, meski tadinya produk ini mulai populer di pasar. Akhirnya importirnya mengajukan permohonan label halal dari LPPOM-MUI.
Pola seperti itu sepertinya akan terus terjadi. Akibatnya, pengusaha makanan mau tidak mau harus mendapatkan sertifikasi halal. Kalau tidak, mereka terancam akan dijauhi oleh konsumen. Atau, lebih parah lagi, dimusuhi.
BreadTalk dan JCo adalah pengecualian. Keduanya hingga saat ini bertahan tanpa sertifikasi halal. Gerai-gerai kedua perusahaan ini tetap ramai dikunjungi pelanggan. Sejak muncul di tahun 2003 kedua produk ini segera digemari pelanggan. Sejak awal sudah beredar pertanyaan tentang kehalalan produk ini. Ada potensi penjualan mereka akan turun kalau tidak bersertifikasi halal. Tapi pengelolanya tetap memilih untuk tidak mengambil sertifikasi. Sejauh ini mereka baik-baik saja.
Apakah setiap produk wajib punya label halal? Menurut UU No. 33 tahun 2014 setiap produk terkait makanan wajib punya sertifikasi halal sejak Oktober tahun 2019. Artinya untuk saat ini dan masa lalu tidak ada kewajiban. Lagipula, penerbit sertifikat menurut amanat UU ini adalah BPJPH, sebuah lembaga di bawah Kementerian Agama, bukan LPPOM-MUI seperti sekarang. Jadi, label halal yang diterbitkan LPPOM-MUI saat ini sama sekali bukan kewajiban. Pihak LPPOM-MUI juga menegaskan soal itu.
Apakah produk yang tidak bersertifikasi dan berlabel halal adalah haram? Tidak. Anda beli jagung bakar di pinggir jalan. Adakah sertifikat halalnya? Tidak. Anda makan di warung padang, apakah warung itu bersertifikat halal? Tidak. Apakah produk-produk itu haram karena tidak bersertifikat? Tidak. Demikian pula dengan produk-produk lain. Tidak ada satu pihak pun yang berwenang menyatakan suatu produk haram. Faktanya, di pasar kita sebenarnya produk tanpa label halal jauh lebih banyak daripada produk berlabel halal.
Kenyataan itu membuat implementasi UU tadi menjadi sulit. Benarkah pemerintah akan mewajibkan semua produk makanan berlabel halal? Bayangkan, ada berapa juta produk yang harus diuji oleh BPJPH. Sanggupkah? Mustahil.
Orang bisa ribut terhadap produk roti atau mie yang tidak bersertifikasi halal, tapi tenang saja dengan produk rendang atau gado-gado yang tidak bersertifikasi halal. Kenapa? Karena ini sebenarnya bukan soal halal haram. Ini soal kenyamanan saja.
Secara prinsip sebenarnya mempertanyakan kehalalan suatu produk berbasis pada prasangka adalah hal yang tidak dianjurkan dalam Islam. Anda makan sepotong roti, tidak perlu Anda bertanya apakah roti itu halal. Secara prinsip sepotong roti itu halal sampai terbukti ia mengandung bahan yang diharamkan. Poin terpenting dalam hal ini adalah, Anda tidak perlu mencari-cari bukti keharaman itu. Itu justru dilarang dalam Islam.
Sikap yang berkembang di masyarakat sekarang justru sebaliknya. Orang-orang didorong untuk mempertanyakan kehalalan produk yang mereka makan. Produk-produk yang mereka pertanyakan kemudian digolongkan sebagai syubhat (meragukan) sampai produk itu terbukti halal, melalui sertifikasi tadi. Anehnya, itu hanya berlaku untuk produk tertentu.
Sekali lagi ini bukan soal halal haram. Ini adalah soal pola pikir sekelompok orang dalam masyarakat, yang bisa disetir ke arah tertentu. Ini adalah soal public relation. Bila Anda kebetulan memiliki produk yang tidak bersertifikasi halal, Anda tidak perlu khawatir ketika produk Anda dipertanyakan. Hal pertama yang harus Anda yakini adalah produk Anda tidak serta merta haram karena tidak memiliki sertifikat halal. Yang perlu Anda lakukan adalah melakukan kegiatan public relation yang baik, sehingga tidak terbentuk citra bahwa produk Anda haram.
Bagaimana teknisnya? Mendiamkan, atau hanya menjawab seperlunya mungkin sebuah tindakan yang bijak. Isu seperti ini biasanya hanya sementara. Mendiamkannya bisa membuat isu ini berlalu dengan segera. Menanggapinya justru berpotensi membuat isunya jadi besar, dan lebih merugikan Anda. Tentu saja ada potensi penurunan penjualan karena itu. Tapi menurut saya, sebaiknya Anda menerima risiko itu, ketimbang mencoba membantahnya, tapi justru berbalik menjadi blunder.
Setelah semua itu berlalu, Anda bisa melakukan upaya-upaya promosi untuk mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan yang sempat menurun. Percayalah, kualitas produk dalam hal cita rasa, kandungan gizi, efeknya bagi kesehatan, serta pelayanan yang Anda berikan, jauh lebih kuat efeknya untuk merebut kepercayaan pelanggan. Saat itu justru jadi momen yang baik untuk melakukan positioning. Anda bisa mempertegas, bahwa target pasar Anda adalah orang-orang yang tidak repot dengan urusan label halal. Pasar yang berisi orang-orang seperti itu sangat besar, Anda tidak perlu takut kehilangan pembeli.